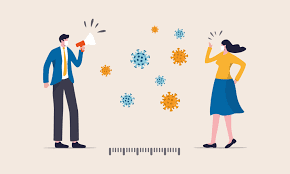Teman DRYD,
Pasti pada familiar dengan jargon “Anak cowo deketnya ama mama, anak cewe ama papa”, kan? Ini tuh anggapan lazim di kalangan masyarakat luas dan emang pas diamati, ada kecenderungan demikian. Tapi sebenernya sejauh apa sih, anggapan ini validitasnya? Apa emang ada penyebab-penyebab khusus atau ini cuma kerangka pikir yang terbentuk berdasar landasan sosiokultural aja?
Naaah, ini nih, yang bakal kita bahas kali ini.
Kalo kita bicara tentang kedekatan antara orang tua dan anak, itu ga jauh-jauh larinya dari proses bonding. Ikatan antara orang tua dan anak terbentuk sejak dini, bahkan sudah dimulai sejak si buah hati masih ada dalam kandungan. Prosesnya sangat fundamental sifatnya dan sering banget ga bisa diobservasi secara langsung. Itu bisa disebabkan karena ada faktor familiaritas antara orang tua dan si anak, jadi semua terasa natural bahkan ketika sekalipun interaksi yang ada tidak secara sadar diarahkan pada pola pembentukan ikatan antara kedua pihak. Tapi saking fundamental proses ini, semuanya bisa berdampak pada tumbuh-kembang si buah hati sampai ke saat anak tersebut menginjak usia dewasa nanti. Mulai dari hal-hal kecil seperti cara kita berkomunikasi, berinteraksi, penggunaan kalimat dan intonasi, cara memberikan komunikasi fisik sampai ke hal-hal yang secara signifikan emang ditujukan untuk mendidik si anak seperti memberi masukan dalam hal akademis, memberi pemahaman mengenai tata krama dan sopan santun, menurunkan nilai-nilai budaya dan sosial. Semua ini adalah bentuk-bentuk bonding antara anak dan kedua orangtuanya. Seerat apa ikatan yang terbentuk pada prosesnya akan menjadi faktor penentu apakah si anak akan berkembang dengan relatif sempurna di kemudian hari.
Nah, jargon yang udah kita singgung sebelumnya akan menjadi penghambat besar dalam memberikan pengaruh positif pada anak kalo kita—sebagai orangtua—tidak mencernanya dengan saksama dan menyeluruh loh. Jangan sampai salah kaprah dan menelan jargon itu mentah-mentah tanpa dipelajari terlebih dahulu.
Pada dasarnya, anak itu paling deket sama ibunya, mau anak cowo, mau anak cewe, ketika mereka masih bayi. Ada basis kuat untuk hal ini. Di fase perkembangan sejak lahir hingga beberapa tahun setelahnya, si bayi akan sangat tergantung pada si ibu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya soal nutrisi. Anak bayi makannya apa? Ya air susu ibunya kan? Cuma ibu yang bisa menyediakan kebutuhan seprimer ini. Itu baru soal makan. Gimana perkara lain kayak ganti popok, mandi, ganti baju? Si ibu kan yang paling sering berperan. Emang sih, ada juga ayah yang menjalankan peran ibu, tapi persentasenya jauh lebih kecil daripada alternatif pertama—dan sifatnya pun lebih cenderung berdasarkan kasus aja.
Semakin si anak bertambah usianya, akan ada sedikit pergeseran. Maka jadilah jargon yang kita bahas di awal tadi: Anak cowo sama mamanya, anak cewe sama papanya. Apakah ini proses alami? Apakah ini bentuk adaptasi? Apa ini cuma soal kebiasaan? Yuk, kita cari tahu alasannya.
Kenapa Anak Cewe Lebih Deket ke Papanya?

Bener ga sih, anak cewe lebih deket sama papanya?
Di mata anak perempuan, figur seorang ayah adalah sosok yang bisa memberikan perlindungan untuknya dan juga lebih tegas. Ini bikin si anak cewe merasa lebih aman pas deketan sama papanya. Ini ga otomatis berarti ibu ga mampu melindungi anak cewe-nya lo ya. Cuma, anak perempuan bisa mendapatkan lebih banyak pelajaran tentang ketegasan dan ketangguhan dari ayahnya.
Faktor lain penyebab anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya adalah kecemburuan terhadap adik, terutama adik laki-laki. Kehadiran bayi baru yang belum bisa apa-apa akan menyedot fokus dan tenaga ibu. Otomatis, anak perempuan yang sudah lebih dewasa umurnya akan mencari sumber perhatian lain karena waktu ibunya sudah terpakai mengasuh sang adik. Dalam hal ini, ayahlah yang menjadi tempat mereka “melarikan diri”.
Riset oleh Jennifer Mascaro di Universitas Emory menunjukkan bahwa seorang ayah juga cenderung lebih mudah memberikan perhatian atau respons untuk anak perempuannya. Hasil riset tersebut membuktikan bahwa aktivitas otak ayah akan meningkat secara signifikan ketika melihat foto anak perempuannya ketimbang anak laki-laki. Secara tidak sadar, ini juga dapat diobservasi dari cara anak perempuan mendekati ayahnya ketika menginginkan sesuatu seperti mainan, misalnya. Si anak perempuan seolah mengerti bahwa ayahnya pasti akan memberikan respons positif terhadap keinginannya ketimbang ibu. Kecenderungan yang ada adalah seorang ibu kemungkinan besar akan mengabaikan rengekan anak perempuannya sementara seorang ayah akan segera mengabulkan permintaannya.
Kenapa Anak Cowo Lebih Deket ke Mamanya?

Anak cowo lebih mesra dengan ibunya, katanya.
Anak cowo akan memilih untuk mengadu atau lari ke ibunya ketika berbuat salah atau menangis karena sesuatu, bukan ke ayahnya. Ini bukan semata-mata soal manja loh, ya. Tapi si anak laki-laki merasa lebih bisa tenang dan diperhatikan oleh ibunya. Kecenderungan yang ada adalah seorang ayah mungkin malah akan menghakimi si anak cowo, bukannya menenangkan. Faktor segan dan takut juga ikut ambil bagian karena seorang papa biasanya punya ekspektasi yang terlalu besar untuk dipenuhi oleh si anak cowo: Laki-laki harus kuat. Padahal justru sebaliknya, kuat-tidak seorang anak tidak dipengaruhi oleh jenis kelaminnya. Anak laki-laki boleh aja kok ngerasa tidak berdaya dan membutuhkan bantuan atau dukungan. Sebaliknya, anak perempuan juga ga boleh kalah dari anak laki-laki, juga harus mandiri dan dependable. Ketegasan seorang ayah pun bisa diartikan sebagai sikap galak oleh anak laki-laki yang mungkin pada suatu waktu tertentu membutuhkan ayahnya.
Kecerdasan emosional seorang anak cowo biasanya terasah lebih baik ketika di dekat mamanya. Anak-anak cowo yang memiiki ikatan kuat dengan mamanya umumnya lebih terjauhkan dari masalah denga teman, tidak suka bertikai atau memilih cara kekerasan seperti berkelahi, tidak ikut-ikut geng sekolahan, tidak jatuh dalam pengaruh narkoba, dan terhindar dari perilaku seks bebas. Tentunya banyak faktor lain yang menentukan ini semua, tidak semata-mata hanya karena kedekatan dengan ibu. Tapi seorang ibu biasanya lebih mudah berkomunikasi dengan anak sehingga si anak laki-laki akhirnya mencontoh sifat ini untuk diterapkan di dalam hidupnya sendiri. Dengan skill komunikasi yang terlatih relatif dengan baik, anak cowo biasanya punya lebih banyak teman dan minim risiko mengalami stres.
Pola kedekatan dengan si ibu juga mempengaruhi anak laki-laki dalam hal berempati, menjauhkan diri dari bahaya, dan pengendalian emosi. Ada juga kemungkinan besar bahwa si anak akan lebih mampu menghargai perempuan.
Salahkah Pola Bonding Seperti Ini?
Ga ada yang salah, ga ada yang benar. Agak berisiko kalo kita mau membedah topik ini dari sudut pandang benar-salah. Yang sebaiknya dilakukan adalah menyudahi pola asuh dan pola didik yang terlalu berbasi gender. Jenis kelamin tidak memainkan peran dalam porsi pemberian kasih sayang dan perhatian—bahkan bukan sebuah faktor yang relevan untuk sekadar dipertimbangkan. Mau anak cowo, mau anak cewe, semua butuh kasih sayang dan apalah kita orang tua kalo bukan gudangnya kasih sayang untuk anak-anak kita, kan? Rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta, dan perhatian itu bukan konsep berbasis gender jadi siapa kita mau menentukan anak cowo porsinya lebih sedikit dari anak cewe atau sebaliknya? Jangan pilih kasih, apalagi pilih kasih berdasar jenis kelamin si anak. Dampaknya bisa fatal dan mungkin ga bisa diperbaiki.
Jangan juga mengandalkan jargon-jargon umum tanpa mendidik diri sendiri sebagai orang tua. Siapa, aturan mana, hukum seperti apa yang menentukan anak mana deket ama ortu yang mana. Anak cewe dan ibunya bisa jadi duo maut yang sinkron di segala lini karena mereka berbagi jenis kelamin yang sama dan begitu juga anak cowo bisa jadi “partner in crime” yang koheren untuk ayahnya karena mereka bisa aja berbagi passion serupa—ini kalo emang mau bawa-bawa jenis kelamin ke perihal bonding, ya. Kalo bonding didasarkan pada jargon semata, efeknya bisa membuat anak punya jarak yang lebar dengan salah satu orang tua. Yang kita mau kan, semua anak kita bisa deket sama kita, kan? Bisa berbagi dengan kita, bisa bicara apa aja sama kita, bisa lengket dan harmonis relasinya dengan kita, kan? Iya, kan? Apa di antara Teman DRYD yang menginginkan sebaliknya? Engga, kan?
Nah, mending dari awal disadari deh. Kontrol jarak antara kita dan buah hati. Kalo dirasa interaksi antara anak cowo dan papanya kurang ato kalo anak cewe kayanya lebih sering hangout sama papanya, coba deh, mulai diliat lagi bagian mana yang harus dimodifikasi.
Semuanya harus rata. Anak cowo harus diajari empati dan cara berkomunikasi oleh ibunya sambil tetap diberikan pemahaman tentang menjadi kuat dan tegas oleh ayahnya dengan cara yang tepat. Anak cewe gimana caranya tetap menyerap nilai-nilai prinsipil dan mendapat perlindungan dari ayahnya tanpa mengecilkan peran si ibu yang bisa mewariskan ajaran tentang keperempuanan padanya. Semua harus balance.
Taaapiii, jangan juga terus lupa sama satu hal yang paaaling fundamental soal mengasuh anak: Setiap anak lahir dengan karakternya masing-masing. Ini juga yang bikin pola asuh berbasis gender dan jargon jadi ga efektif. Setiap anak adalah “special case”, pendekatannya seharusnya lebih ke berbasis individual dan sesuai porsi dan posisi. Kita sebagai orang tua harus siaga buat beradaptasi dengan karakter anak sambil tetap diarahkan. Harus fluid dan fleksibel. Harus adaptif. Harus siap dengan perubahan dan mau menerima hal-hal baru selain dari jargon atau quote tua yang belum tentu aplikatif di era modern ini.

Anak cowo atau cewe sama-sama butuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.