
Hai Teman DRYD,
Mungkin di antara teman semua ada yang memahami apa itu bias gender dan tahu pasti tentang literatur atau sumber-sumber padat informasi mengenai isu satu ini. Mungkin ada yang tahu tapi pemahamannya masih samar, masih meraba-raba. Jadi ada baiknya jika pertemuan kita kali ini diawali dengan pembahasan yang mendasar dulu ya.
Yuk, kita samakan persepsi dulu mengenai definisi istilah itu. Bias adalah suatu kondisi yang diwarnai dengan kecenderungan untuk memihak atau merugikan. Gender adalah sifat atau nilai yang dilekatkan baik pada laki-laki maupun perempuan oleh konstruksi sosial dan budaya. Dari sini, kita bisa mensederhanakan pengertian bias gender menjadi keberpihakan pada satu gender yang merugikan gender lain.
Gender tidak sama dengan jenis kelamin ya, moms, sekalipun sering digunakan bergantian dengan anggapan bahwa keduanya merupakan sinonim. Kata kuncinya adalah ‘sosial’ dan ‘budaya’. Gender merupakan identitas hasil persepsi sosial dan ditanamkan pada satu individu dalam ruang lingkup kultur tertentu. Dan karena berkaitan dengan kultur, maka identitas gender bisa dikatakan sebagai warisan leluhur sebab ide mendasar yang menjadi landasan pembagian gender muncul dan diteruskan secara turun-temurun.
Akibatnya apa? Kita sebagai masyarakat sosial memiliki kebiasaan untuk mengkotak-kotakkan sesuatu berdasar ide identifikasi gender tersebut. Contohnya apa, Dok? Misal nih, pas lebaran kan ada tradisi beli baju baru kan. Nah, orang tua akan cenderung memilih produk yang dibeli berdasar pola gender tadi. Jadilah anak laki-laki dibelikan baju biru sementara anak perempuan dapat baju warna merah jambu. Atau anak laki-laki dibelikkan robot-robotan sementara adik perempuannya diberi boneka cantik yang anggun. Ga ada salahnya sama sekali melakukan yang seperti ini—asal anaknya seneng aja. Tapi, coba deh lihat kembali ke belakang, apa sih yang mendasari perlakuan seperti ini? Anak-anak mungkin ga peduli dengan konsep seabstrak maskulin-feminin dan itu lumrah karena mereka belum perlu mengenal keduanya dan apa bedanya. Kita nih, sebagai orang tua yang menyetir persepsi mereka dari kecil sehingga mainan mobil-mobilan merupakan hak prerogatif untuk laki-laki sementara anak perempuan diidentifikasi dengan boneka, warna merah jambu, permainan masak-masakan, dan sederet lain aktivitas yang dinilai cewe banget.
Emang secara lahiriah cowo–cewe itu beda. Tapi siapa yang tahu pasti tentang perkara batiniah. Seorang anak perempuan mungkin tertarik memegang robot-robotan karena di matanya robot itu sangat unik untuk dieksplorasi ketimbang boneka sederhana yang membosankan. Seorang anak mungkin tertarik dengan warna biru atau merah elektrik atau bahkan hitam karena entah kenapa. Itu cuma preferensi ya, Teman-teman. Memilih sesuatu yang diidentikkan dengan lawan gendernya tidak serta-merta mengubah identifikasi seksualnya. Si anak perempuan cuma suka main robot, ga ada yang salah kan? Bias gender-lah yang membuat semua terlihat seperti tidak pada tempatnya.
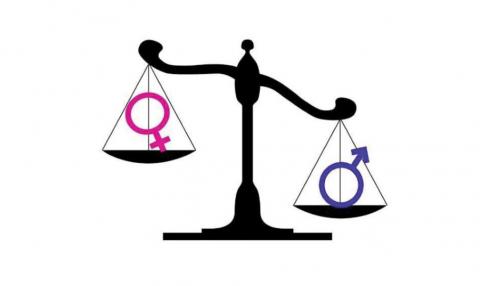
Guys, otak kita merespon konsep bias dengan sangat baik. Konsep maskulin-feminin dan strata di antara keduanya merupakan konsep purba yang sudah dipupuk selama ratusan ribu tahun sejak nenek moyang kita masih hidup di gua dengan pola berburu dan meramu. Kebayang kan, seberapa dalam pemahaman ini udah mengakar di dalam gen kita? Otak kita kayak udah disetel demikian dari sananya. Ini adalah kultur yang patut untuk ditilik lebih lanjut untuk direkonstruksi. Kenapa? Yang berbahaya lagi adalah kebiasaan pengelompokan hal berdasar gender ini akan lambat laun membentuk karakter si anak. Berdasarkan pengertian bias gender menurut para ahli, pihak gender yang diuntungkan akan mudah melontarkan judgment sementara si pihak yang dirugikan akan memiliki kompleks inferioritas. Kita sebagai orang tua pastinya ga mau kan, kalo ada anak kita yang merasa dirinya inferior? Karena bias gender lebih sering merugikan perempuan ketimbang laki-laki, maka jika pola asuh berdasar gender diterapkan secara asal, anak perempuan bukan ga mungkin akan merasa lebih kecil daripada laki-laki. Lebih jauh lagi, inferioritas ini mungkin berpotensi merambah lebih dalam lagi dan membuat si anak merasa kecil di hadapan siapapun bahkan di depan sesama gendernya sendiri. Orang tua yang paling memanjakan anaknya sekalipun pasti ingin anaknya mandiri dan mampu menyelesaikan persoalannya sendiri dengan relatif lancar. Sekarang, kalo dari awal aja si anak udah ngerasa ga mampu, gimana gedenya, kan?
Yang lebih menyedihkan lagi adalah keberadaan bias gender dalam pendidikan. Sekolah, sebuah institusi pendidikan formal, pun mengaplikasikan bias gender, disadari atau tidak. Buku-buku pelajaran diwarnai dengan pengondisian konseptual terhadap peran laki-laki versus perempuan. Di buku-buku SD—bahkan mungkin sarana pengajaran di playground—coba liat deh. Anak laki-laki diilustrasikan bermain di luar rumah dengan teman-temannya. Atau mungkin mancing dengan bapaknya. Atau mungkin ada ilustrasi lain yang menggambarkan pria dewasa di lingkungan kerjanya. Bagian anak perempuan gimana? Anak cewe biasanya digambarkan membantu ibunya memasak di rumah, beres-beres kamar, bermain boneka sendirian. Perempuan dewasa diilustrasikan sebagai pribadi yang terikat dengan rumah: Mengasuh anak, menyiapkan makan dan minum, atau mungkin ngobrol sama tetangga. Jomplang kan? Dan itu ditemukan di media pendidikan dasar yang akan membentuk landasan pikiran dan persepsinya di kemudian hari.
UUD 1945 pasal 31 udah dengan sangat gamblang ngasi ketegasan: Pendidikan itu hak semua warga negara. Ga peduli gendernya. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang setara maka buku pelajaran SD pun sebaiknya bisa memuat ilustrasi tentang seorang pilot perempuan. Pernah liat perempuan jadi pilot? Kalopun pernah pasti cuma sekali seumur hidup dan tanggapan kita pasti, “Gilak ni cewek, jadi pilot euy!” Ada perasaan takjub campur heran. Tapi kalo kita liat pilot laki-laki, apa respons kita? Ga ada kan? Seolah-olah kita udah nerima gitu aja kalo pilot itu pekerjaan yang secara natural dilakukan laki-laki. Artinya apa? Secara ga langsung kita dikondisikan untuk beranggapan bahwa cuma laki-laki yang punya kecakapan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk menjadi pilot.

Okelah kita berargumen memang perempuan memiliki fisik yang lebih lemah dari laki-laki sehingga wajar yang dipilih untuk satu pekerjaan adalah laki-laki. Oke, let’s go with that argument. Tapi itu tidak otomatis menutup pintu probabilitas seharusnya. Laki-laki dan perempuan berhak atas pengetahuan yang sama, dalam komposisi yang sama, dengan persepsi yang sama, dan perlakuan yang sama dalam hal pendidikan. Kita ambil contoh profesi pilot tadi. Aturan mana yang melarang perempuan untuk mempelajari dunia penerbangan? Terserah nanti di masa depan mau kayak gimana. Seorang perempuan akan menjadi pilot atau tidak, itu tergantung ketekunan, potensi, preferensi, dan kemampuannya. Tapi paling tidak sedari awal dia sudah dibekali dengan porsi pengetahuan yang ga beda dari rekan laki-lakinya.
Apa akibatnya kalau kita membiarkan bias gender menjadi that one driving force di balik cara kita mengasuh anak? Banyak. Terlalu banyak untuk dibahas karena sifatnya sistemik, menjalar ke mana-mana. Tapi secara umum bias gender dalam pola asuh bisa:
- Membuat si anak berkembang menjadi pribadi yang mudah memberikan judgment pada pihak yang tidak menerapkan konsep yang serupa. Contoh nih, si anak A melihat sebuah keluarga yang bapaknya ga Si ibu yang mencari nafkah sementara si bapak mengasuh anak dan mengurus rumah. Si A akan memiliki persepsi negatif terhadap keluarga tersebut. “Ih, masa cowo ga kerja…?” “Ih, kok cewe berangkat pagi pulang sore. Apa ga mau ngurus rumah ya?” Kita ga pernah tahu cerita yang ada di balik sebuah keluarga. Dan bias gender membuat kita merancang sebuah cerita tentang keluarga itu untuk merasionalisasi ketidakcocokan dengan konsep pribadi kita.
- Menghambat fleksibilitas anak ketika nanti dewasa. Contoh yang paling mudah adalah tentang pilot yang tadi kita bahas. Karena sedari kecil udah diinternalisasikan ke pikiran si anak cewe bahwa dia ga punya kepantasan untuk menyandang gelar profesi tertentu, sedari kecil jalan hidupnya bakal banyak benturan. Dia akan berjalan di satu arah tertentu yang didiktekan oleh konstruksi sosial budaya sekitarnya. Tidak ada ruang untuk bertumbuh dan berkembang dan menyerap pengalaman lain. Perempuan dituntut untuk selalu bersifat melayani, berpembawaan lembut, dan selalu berpenampilan cantik. Dan tidak ada pilot (atau profesi lain yang terasa maskulin) dikondisikan tidak cocok untuk yang cantik-cantik atau yang lembut-lembut. Profesi itu cuma cocok untuk yang gagah, kuat, dan berani, yaitu segala kualitas yang dimiliki laki-laki. Potensi yang mungkin ada di diri satu gender akan ditekan sangat kuat oleh sosial budaya di sekitarnya hanya karena tidak dinilai sesuai.
Kesetaraan gender tidak otomatis meninggalkan kodrat masing-masing individu. Iya, emang perempuan dikaruniai insting lebih serta desain fisik yang membuatnya mampu menjalankan peran sebagai ibu. Tapi mengasuh anak tidak serta-merta menjadi ranah khusus perempuan. Si bapak tidak harus melulu bekerja, minta dilayani, dan istirahat. Kalo emang ada waktu dan energi, coba deh, ambil si anak dari pangkuan istri dan ajak main. Itung-itung ngasi istri jeda buat bernapas. Bonding akan menjadi proses yang menyenangkan sehingga si anak tidak berkembang menjadi pribadi yang menganggap bapaknya seseorang yang kaku, dingin, dan tidak bisa diakses. Anak itu seharusnya punya akses 24 jam bebas hambatan loh, ke orang tuanya sendiri. Ini penting untuk membangun kedekatan dan menciptakan keharmonisan.
Sistem keluarga patriarki memang sudah terlalu kental dalam struktur sosial masyarakat kita. Butuh proses panjang dan ketekunan untuk bisa menyusun ulang semuanya supaya ga ada pihak yang dirugikan. Tapi semua mulainya dari keluarga inti kok. Jadi apa yang bisa kita lakukan?
Pertama, biarkan preferensi menjadi preferensi. Sadari bahwa preferensi bukanlah sebuah tindakan yang melawan hukum alam. Biarkan anak-anak memilih apa yang mereka suka; toh, kalau nantinya mereka tidak lagi merasa cocok dengan suatu hal, mereka akan mencari hal lain lagi yang barangkali lebih sesuai. Sambil tetap diamati loh, ya. Jangan sampe kebablasan melanggar koridor kewajaran. Anak yang cewe penasaran sama mobil-mobilan abangnya, berikan ia kesempatan untuk eksplorasi. Anak cowo mau nyoba megang boneka kakaknya, biarin ya, moms. Cuma megang doang, ga perlu ditanggapi dengan histeris apalagi sampe keluar pertanyaan, “Anak laki main bonekaaa? Mau jadi apa kamu?!” Ga perlu ya, moms. Dia cuma penasaran dan membiarkan anak menemukan jawaban atas rasa penasarannya akan berdampak positif untuk tumbuh-kembang-nya.
Kedua, jangan pilih kasih. Anak cowo dibeliin baju baru warna biru, tanya saudara perempuannya apa mau warna biru juga? Lagi-lagi, jangan membatasi preferensinya. Kecuali kalo emang dianya memilih yang berbeda. Tapi tanyakan dulu maunya apa dan yang mana. Dengan begini dia bisa merasakan kenyamanan dalam lingkup keluarga yang inklusif dan paham bahwa orang tuanya tidak memilih-milih dalam meberikan perhatian. Ini juga berlaku untuk keluarga dengan satu anak loh, ya. Biarkan anak yang memilih, kita cuma perlu kasi pendapat tanpa memaksakan konsep apapun. Toh, yang make barangnya ya dia. Toh, yang ngejalanin hidupnya nanti ya dia. Kita cuma perlu membiarkan dia tahu bahwa kita sangat menyayanginya.

